
Oleh: Hamdani S Rukiah, SH, MH*
DUA kasus kekerasan seksual baru-baru ini mengguncang kepercayaan publik terhadap dua institusi besar di Indonesia: rumah sakit dan perguruan tinggi. Seorang dokter residen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung ditangkap polisi setelah diduga memperkosa keluarga dari pasien.
Sementara itu, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hanya dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan fungsional dan tugas tridarma perguruan tinggi, meskipun laporan menyebutkan bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa di bawah bimbingannya.
Kontrasnya penanganan dua kasus tersebut menimbulkan pertanyaan publik: mengapa penegakan hukum bisa begitu cepat dalam satu kasus, namun lamban dalam kasus lain? Apakah ini soal keberanian korban untuk melapor, kekuatan bukti, atau ada perbedaan struktur hukum yang memang memperlakukan kedua tindak kekerasan seksual itu secara berbeda?
Delik Biasa vs Delik Aduan, Kunci Perbedaan Proses Hukum
Secara hukum, memang terdapat perbedaan signifikan antara pemerkosaan yang dituduhkan kepada dokter di RSHS dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru besar UGM. Kasus pemerkosaan masuk dalam kategori delik biasa. Artinya, penegak hukum bisa memproses perkara ini tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan resmi dari korban. Ketika ditemukan cukup bukti seperti visum, rekaman CCTV, atau saksi yang relevan, polisi dapat segera bergerak dan menetapkan tersangka.
Baca juga: Apa Arti Hukuman Mati Jika Tak Bisa Dieksekusi?
Hal inilah yang terjadi dalam kasus dokter RSHS, di mana polisi bahkan menyatakan ada dugaan penggunaan zat anestesi yang membuat korban tidak sadarkan diri—menambah bobot dugaan kejahatan tersebut.
Sebaliknya, kasus yang melibatkan guru besar UGM lebih kompleks secara hukum. Dugaan pelecehan seksual dalam lingkungan akademik kerap masuk dalam kategori delik aduan, terutama jika tidak terjadi kontak fisik secara paksa atau pemaksaan hubungan seksual secara langsung. Dalam konteks ini, korban harus secara aktif melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian agar proses hukum dapat berjalan.
UU TPKS dan Realitas Implementasi di Lapangan
Sejatinya, undang-undang sudah memberi ruang untuk menindak tegas berbagai bentuk kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemerkosaan dalam Pasal 285 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dalam posisi kuasa seperti guru atau dosen terhadap peserta didik diatur dalam Pasal 294.
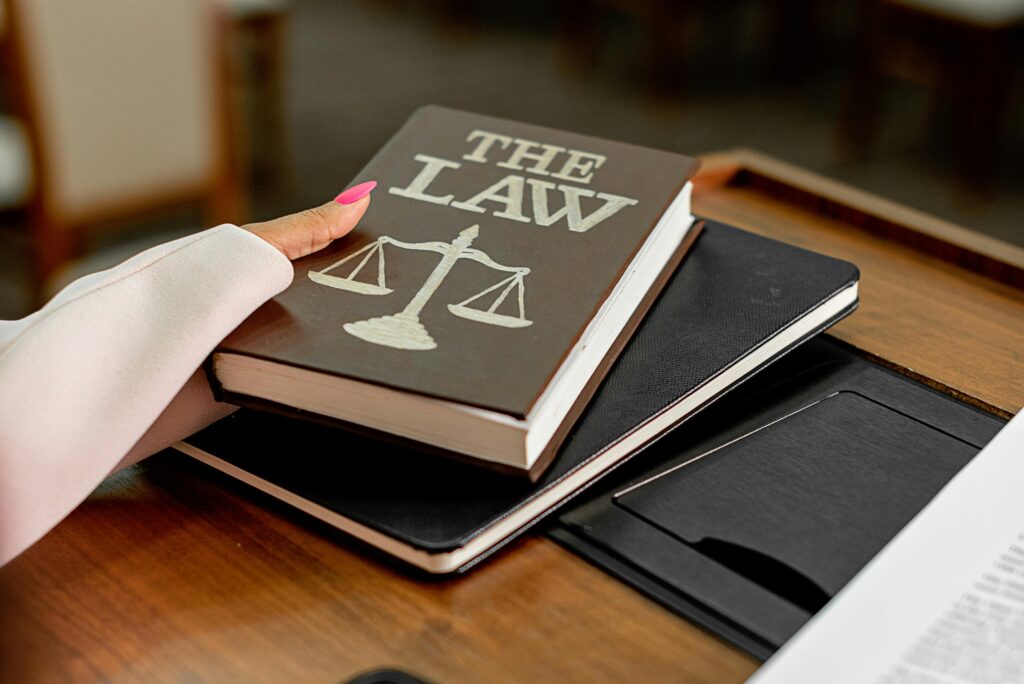
Selain KUHP, Indonesia kini memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022), yang secara komprehensif mengakui beragam bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan, perundungan seksual, pemaksaan relasi, dan kekerasan berbasis gender. Dalam UU TPKS, kekerasan dalam relasi kuasa—misalnya antara dosen dan mahasiswa—diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang bisa diproses secara hukum.
Baca juga: Tanah untuk Rakyat, Bukan Hanya Segelintir Orang
Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan besar. Banyak institusi pendidikan belum sepenuhnya membangun sistem yang mendukung pelaporan kasus kekerasan seksual secara aman dan berpihak pada korban. Selain itu, aparat penegak hukum juga kerap kali menunggu tekanan publik sebelum bertindak tegas.
Peran Publik, Media, dan Institusi: Jangan Tunggu Viral
Dalam kasus dokter RSHS, sorotan media dan tekanan publik mendorong aparat bergerak cepat. Begitu pula kasus guru besar UGM. Ketika laporan investigatif internal kampus mencuat ke media dan menjadi viral, barulah publik mendesak adanya penindakan lebih tegas. Ini menandakan bahwa kekuatan publik, media, dan masyarakat sipil sangat berperan dalam membentuk respons institusi terhadap kekerasan seksual.
Baca juga: Bencana Ekologis Jabodetabek, Mengapa Pejabat Tak Pernah Dipidana?
Sayangnya, tidak semua korban memiliki keberanian atau kekuatan untuk membawa kasusnya ke ruang publik. Oleh karena itu, penting bagi institusi seperti kampus untuk tidak hanya membentuk satgas PPKS sebagai formalitas, tetapi juga memastikan adanya perlindungan nyata bagi korban dan kolaborasi aktif dengan aparat penegak hukum.
Keadilan Jangan Bergantung pada Viralitas
Kita tidak bisa berharap keadilan datang hanya saat kasus viral. Hukum seharusnya tidak tunduk pada popularitas isu, melainkan berdiri atas prinsip keadilan dan perlindungan korban. Tanpa itu, kita hanya akan terus menyaksikan ketimpangan dalam perlakuan terhadap kasus kekerasan seksual—di ruang medis, akademik, bahkan di ruang-ruang yang seharusnya paling aman. ***
- Jurnalis, pemerhati keadilan sosial, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.