
Oleh: Hamdani S Rukiah, SH, MH *
SERATUS satu tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Lahir dari ruang kelas kolonial bernama Rechtshogeschool di Batavia (kini Jakarta, red) pada 28 Oktober 1924.
Dulu, mahasiswa hukum belajar dengan pena dan pasal.
Kini, generasi baru belajar dengan ponsel dan prompt.
Dunia hukum sudah berjalan lebih dari satu abad, tapi tantangannya justru baru dimulai.
Dulu, hukum berhadapan dengan kekuasaan.
Sekarang, hukum berhadapan dengan algoritma.
Dan pertanyaannya sederhana.
Apakah pasal-pasal lama masih bisa menegakkan keadilan di dunia yang dikendalikan data?
Dari Pena ke Prompt
Mahasiswa hukum dulu menulis argumentasi di atas kertas.
Sekarang, mereka menulis lewat layar, di mana ChatGPT bisa menjawab dengan cepat, bahkan kadang lebih cepat dari dosennya sendiri.
Baca juga: Pengacara Didenda Rp166 Juta Gara-gara Kutip Kasus Fiktif dari ChatGPT
Tapi di sinilah paradoksnya.
Teknologi mempercepat akses pada hukum, tapi juga memperlemah proses berpikir kritis di baliknya.
Kalimat yang dihasilkan mesin mungkin benar secara tata bahasa, tapi apakah juga benar secara nurani?
Hukum seharusnya bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang etika.
Dan di tengah banjir informasi, etika itulah yang sering tenggelam.
Pasal demi pasal bisa dihafal, tapi empati tidak bisa diunduh.
Saat Pasal Bertemu Algoritma
Bayangkan, algoritma media sosial kini bisa menentukan opini publik, bahkan memengaruhi putusan di ruang sidang lewat tekanan digital.
Deepfake bisa memanipulasi bukti, AI bisa menulis pledoi, dan data bisa menggantikan saksi mata.
Hukum dihadapkan pada realitas baru yang tidak pernah dibayangkan para perintisnya.
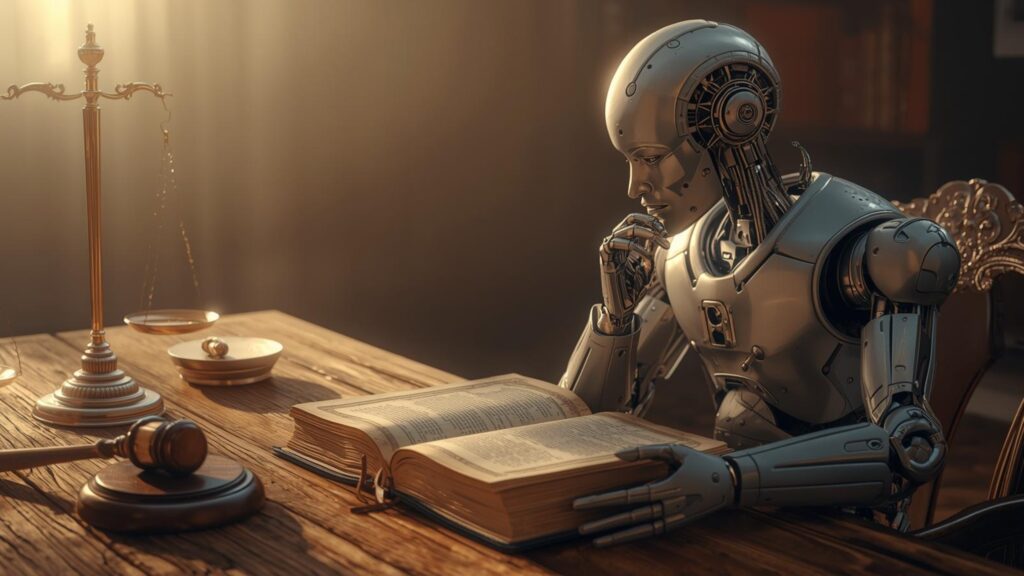
Di sinilah pendidikan hukum kita diuji.
Apakah fakultas hukum masih sibuk dengan teori klasik tanpa bicara etika digital, hak privasi, atau tanggung jawab platform?
Apakah mahasiswa hukum masih disiapkan untuk menghadapi pengadilan, atau juga ruang siber tempat reputasi seseorang bisa “dihukum” sebelum sidang dimulai?
Keadilan di Era Viral
Dulu keadilan dicari lewat berkas perkara.
Sekarang, keadilan bisa lahir dari linimasa.
Satu video viral bisa mengguncang opini publik dan mengubah jalannya kasus.
Tapi siapa yang bertanggung jawab atas keadilan digital ini?
Negara, platform, atau kita semua?
Baca juga: Tinder Swindler Ditangkap, Modus Asmara Bernilai Rp164 Miliar Terbongkar
Mungkin, di usia 101 tahun pendidikan hukum Indonesia, pertanyaannya bukan lagi “apa hukum itu,” tapi “di mana hukum itu hidup.”
Apakah di pasal. Di pikiran hakim. Atau di algoritma yang menentukan apa yang kita lihat dan percayai?
Menatap Abad Kedua
Seratus satu tahun adalah usia matang.
Namun kedewasaan hukum tidak diukur dari usia, tapi dari kemampuannya beradaptasi.
Baca juga: ‘Body Shaming’ di Medsos Bukan Sekadar Candaan, Ada Sanksi Hukumnya
Di abad kedua nanti, fakultas hukum harus berani menulis ulang babnya. Memasukkan etika digital, literasi AI, dan keadilan ekologis ke dalam kurikulum.
Karena masa depan hukum bukan hanya tentang menghafal pasal, tapi memahami manusia, dan mesin yang menjalankannya.
Hukum boleh lahir di masa kolonial.
Tapi, keadilannya harus hidup di masa digital. ***
- Hamdani S Rukiah, SH, MH, adalah Pemimpin Redaksi mulamula.id dan SustainReview.ID.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.